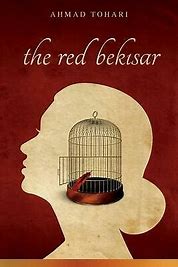Harris Hermansyah Setiajid
Penikmat Buku-buku Terjemahan
Anggota JLTC No. 0039
Christiane Nord adalah salah satu teoretikus penerjemahan yang membela Skopostherie. Dalam berbagai kesempatan, Nord memberikan semacam perbaikan dan pengembangan terhadap Skopostherie. Kritikan terhadap Skopostheorie dijawab oleh Nord dalam bukunya Text Analysis in Translation (1988) yang mengatakan, “walaupun tujuan atau fungsionalitas TSa menjadi kriteria utama sebuah terjemahan, penerjemah tetap tidak diizinkan untuk berbuat semaunya.”
Untuk menjawab kritikan terhadap Skopostheorie, Nord membedakan antara loyalty (loyalitas) dan fidelity (kesetiaan). Dia mengatakan bahwa kesetiaan adalah konsep hubungan yang mengikat antara teks sumber dan sasaran, sementara loyalitas merujuk pada kategori interpersonal antara manusia.
Nord menyebut prinsip tersebut sebagai “fungsionalitas plus loyalitas.” Dengan kata lain, loyalitas adalah tanggung jawab penerjemah kepada mitranya (“pemain” meminjam istilah Holz-Mänttäri). Penerjamah harus bermain “cantik” antara mempertahankan loyalitasnya dan menjaga kesetiaan pada teks.
Selain itu, Nord juga membedakan antara penerjemahan dokumenter (documentary translation) dan penerjemahan instrumental (instrumental translation).
Penerjemahan Dokumenter: berperan sebagai dokumentasi komunikasi budaya sumber antara penulis dan pembaca TSu. Contoh dalam penerjemahan teks sastra, TSa memberikan akses kepada pembaca sasaran untuk mengenali budaya sumber seperti apa adanya, dan pembaca sasaran sadar bahwa yang dibacanya adalah teks terjemahan. Penerjemah memberikan warna “eksotik” kepada teks terjemahannya, misalnya dalam terjemahan cerpen-cerpen Ahmad Tohari, beberapa cultural item tidak diterjemahkan, e.g. mitoni, siraman, dsb.
Penerjemahan Instrumental: berperan sebagai instrumen transmisi pesan dalam budaya sasaran, yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan komunikatif sehingga pembaca tidak sadar sedang membaca teks terjemahan, atau seolah-olah sedang membaca teks yang ditulis dalam bahasa mereka sendiri. Nord menyebut ini sebagai function-preserving translation (bdk. konsep efek kesepadanan Nida). Namun, dia juga memberikan contoh teks terjemahan yang sama sekali berbeda dengan fungsi aslinya, seperti penerjemahan Gulliver’s Travel untuk buku cerita anak.

Nord ternyata tidak berhenti sampai di situ, dalam bukunya Translating as a Purposeful Activity (1997) ia mengajukan model yang lebih fleksibel yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu: (1) pentingnya translation commission (yang kemudian diistilahkannya sebagai translation brief), (2) peran analisis TSu, dan (3) hierarki fungsional masalah penerjemahan.
Pentingnya translation brief.
Sebelum analisis tekstual dilakukan, penerjemah perlu membandingkan profil TSu dan TSa yang ditentukan dalam brief (commission) untuk mendapatkan informasi tentang (1) fungsi masing-masing teks, (2) penulis TSu dan penerima TSa, (3) tempat dan waktu saat penerjemahan dilakukan dan diterima pembaca, (4) media yang digunakan, (5) motif (mengapa TSu ditulis dan mengapa diterjemahkan).
Peran analisis teks sumber.
Analisis TSu untuk memetakan (a) kelayakan penerjemahan, (2) butir TSu yang paling relevan yang perlu mendapatkan perhatian untuk mencapai terjemahan yang fungsional, (c) strategi penerjemahan yang diperlukan untuk memenuhi syarat di translation brief. Nord membuat daftar faktor intratekstual yang harus diperhatikan: (1) subjek penerjemahan, (2) isi, (3) presuposisi, (4) komposisi teks, (5) elemen non-verbal, (6) leksis, (7) struktur kalimat, (8) fitur suprasegmental.
Hierarki fungsional masalah penerjemahan.
Nord merekomendasikan hierarki fungsional saat melakukan penerjemahan, dengan pendekatan atas-bawah dimulai dari perspektif pragmatik dengan fungsi TSa yang diinginkan: (a) perbandingan fungsi TSu dan TSa untuk memutuskan tipe terjemahan yang akan dihasilkan (dokumenter atau instrumental), (b) analisis translation brief untuk menentukan elemen fungsional apa yang akan direproduksi atau diadaptasi sesuai dengan situasi/konteks pembaca sasaran, (c) masalah yang ditemui dalam teks bisa diatasi pada tataran linguistik mikro dengan menggunakan analisis intratekstual TSu.
Penekanan pada pentingnya pembaca sasaran ini membuat pendekatan fungsional, yang lahir dari penyempurnaan Skopostheorie yang disusun Vermeer dan Reiss, menjadi pijakan yang jelas bagi para penerjemah dalam menentukan orientasi terjemahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan fungsional ini membuka dan menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori terjemahan lainnya.
ReferensiHatim, Basil & Munday, Jeremy. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge.
Nord, Christiane (1988). Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Translated by Christiane Nord and Penelope Sparrow. 2nd edition. Amsterdam: Rodopi.
Nord, Christiane. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.
Reiss, Katharina. (2004). ‘Type, kind and individuality of text: Decision making in translation’. Translated by Susan Kitron in Lawrence Venuti (ed.). The Translation Studies Reader. 2nd edition. New York: Routledge.
Reiss, Katharina & Vermeer, Hans (2013). Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained. Translated by Christiane Nord. Manchester: St. Jerome.
Vermeer, Hans (2012). ‘Skopos and commission in translational action’ in Venuti (ed). The Translation Studies Reader. 3rd edition. New York: Routledge.