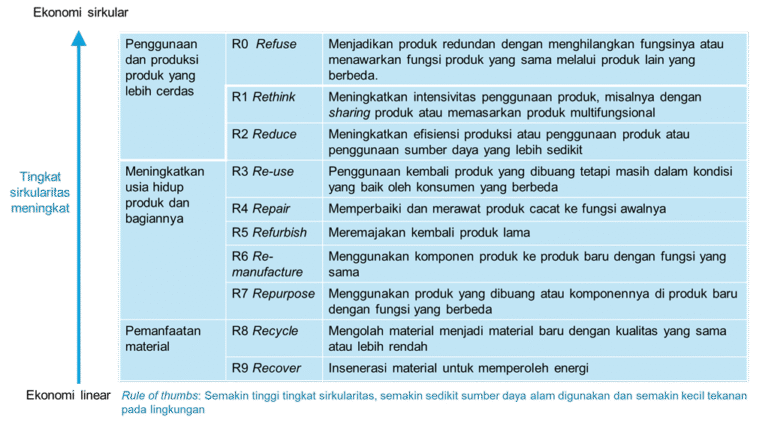Yosephine Suharyanti
Departemen Teknik Industri
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pada situasi sekarang, suatu usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisa serta merta tutup usaha akibat komentar negatif pelanggan di dunia maya, seperti di berbagai platform ulasan dan media sosial. Sebaliknya, komentar positif dapat membuat suatu usaha membesar dalam waktu singkat. Sentimen negatif dan positif yang menetap di platform ulasan seperti Google Reviews dan ulasan dalam lokapasar (marketplace) dapat menjadi rujukan bagi banyak orang yang hendak memanfaatkan produk dan jasa UMKM. Sentimen negatif dan positif yang muncul di media sosial dapat meletup, viral, dan meledak, mampir di beranda berbagai media sosial banyak orang.
Dampak tersebut sangat besar karena pengguna internet dan media sosial Di Indonesia sangat besar. Data pada Februari 2025 (Kemp, 2025) menunjukkan bahwa terdapat 365 juta koneksi telepon seluler di Indonesia (125% populasi), 212 juta orang (74.6% populasi) pengguna internet, dan 143 juta (50,2%) pengguna media sosial.
UMKM harus mulai memandang penting dan memperhatikan ulasan pelanggan di dunia maya untuk berbenah. Bellanov et al. (2020) menyimpulkan dari penelitiannya mengenai analitik data pada antarmuka pelanggan sejumlah lokapasar, bahwa reputasi toko di suatu lokapasar menentukan jumlah pengikut (followers) yang adalah pelanggan setia toko tersebut. Analisis atas ulasan pelanggan di dunia maya dapat membantu UMKM untuk memperbaiki produk dan layanannya. Lebih jauh, mengintip dan menganalisis ulasan usaha sejenis dan menjadikannya dasar perbaikan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan meraih pasar.
Text mining dan bahasa gaul
Sejumlah akademisi dalam bidang-bidang terkait industri mengusulkan dan menciptakan berbagai model, metode, dan alat bantu bagi industri dan UMKM untuk melakukan analisis ulasan pelanggan. Pada umumnya model, metode, dan tools tersebut didasarkan pada text mining. Text mining adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mentransformasikan data mentah berupa teks menjadi data yang berpola sehingga dapat diperoleh informasi berupa pengetahuan atas perilaku di balik data tersebut (Han & Kamber, 2006). Salah satu pekerjaan text mining dilakukan oleh Saraswati et al. (2022) untuk mengidentifikasi faktor dominan yang menentukan minat beli serta analisis sentimen pelanggan UMKM gerai makanan dan minuman, dengan sumber data teks dari Google Reviews.

Kesulitan yang didapat dalam proses text mining terhadap teks yang dibuat oleh banyak orang pada platform non-formal, seperti pada Google Reviews, adalah banyaknya bahasa gaul yang tidak ada dalam kamus. Untuk mendapatkan hasil maksimal, harus dilakukan identifikasi lebih dahulu sebanyak mungkin kosa kata bahasa gaul yang terkait dengan tujuan analisis untuk dimasukkan dalam library aplikasi atau perangkat lunak text mining yang digunakan.
Jika text mining dilakukan untuk teks berbahasa Inggris, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan adalah produk negara-negara berbahasa Inggris, sehingga pemutakhiran library Bahasa Inggris dalam aplikasi atau perangkat lunak tersebut cukup memadai. Sementara itu, yang dibutuhkan oleh UMKM Indonesia adalah analisis atas ulasan berbahasa Indonesia.
Tantangan bagi praktisi bahasa
Sejauh yang dapat diobservasi, belum bisa ditemukan suatu sumber di internet yang dapat memberikan kamus bahasa gaul yang selalu termutakhirkan, sebagai dasar melakukan text mining. Sumber istilah bahasa gaul Indonesia yang dapat ditemukan dan cukup lengkap terdapat dalam Kamus Lengkap (2025), namun masih banyak kosa kata gaul yang sudah digunakan sekian tahun terakhir belum ditemukan, seperti kata ‘fomo’, ‘sus’, ‘delulu’, dan sebagainya. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para praktisi bahasa dan lembaga atau insitusi yang berkutat dengan bahasa.

Selama ini, sumber resmi yang ada adalah Bahasa Indonesia baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2016). Namun bahasa baku tidak cepat berkembang, dan justru tidak terlalu dibutuhkan dalam analisis teks opini orang banyak yang menggunakan bahasa tak baku. Akan sangat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi industri di Indonesia jika para praktisi bahasa bisa membuat suatu kamus bahasa gaul yang lengkap, selalu termutakhirkan, dan dapat diakses publik. Bantuan para praktisi sistem informasi dan informatika dibutuhkan pula untuk mewujudkan kamu bahasa gaul yang berbasis web atau aplikasi.
Sebagai penutup, di situasi sekarang, tidak ada satu ilmu pun yang bisa mandiri untuk menjadi berguna. Kolaborasi dan saling dukung dengan kepakaran masing-masing dibutuhkan untuk menjadikan dunia lebih baik. Jadi, para praktisi bahasa, kapan bergerak menjawab tantangan ini?
https://doi.org/10.5281/zenodo.17066477
Pustaka
Bellanov, A., Suharyanti, Y., & Daryanto, Y. (2020). Applying user interface analytics to identify online shop performance factors. International Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2(2), 49–60. https://doi.org/10.24002/ijieem.v2i2.4797
Han, J., & Kamber, M. (2006). Data mining: Concepts and techniques (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
Kamus Lengkap. (2025). Kamus Bahasa Gaul Indonesia. Kamus Lengkap. https://kamuslengkap.com/kamus/gaul
KBBI VI Daring. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi VI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Kemp, S. (2025, Februari). Digital 2025: Indonesia. Datareportal. https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia
Saraswati, I. D., Suharyanti, Y., & Daryanto, Y. (2022). Food sellers strategy based on customer reviews before and during Covid-19 pandemic in Indonesia. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, 21(1), 74–85. https://doi.org/10.20961/performa.21.1.54954